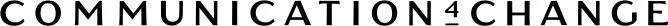Ternyata aksi protes ekstrem malah membuat publik menjauh. Lalu aktivis harus bagaimana?
Untuk mengejar perhatian media dan publik, aktivis kerap merasa perlu melakukan aksi protes yang disruptif. Namun, penelitian menemukan bahwa tindakan ini justru bisa menghambat tercapainya perubahan.
By Macan Wigit
Maret 01, 2024
Maret 01, 2024
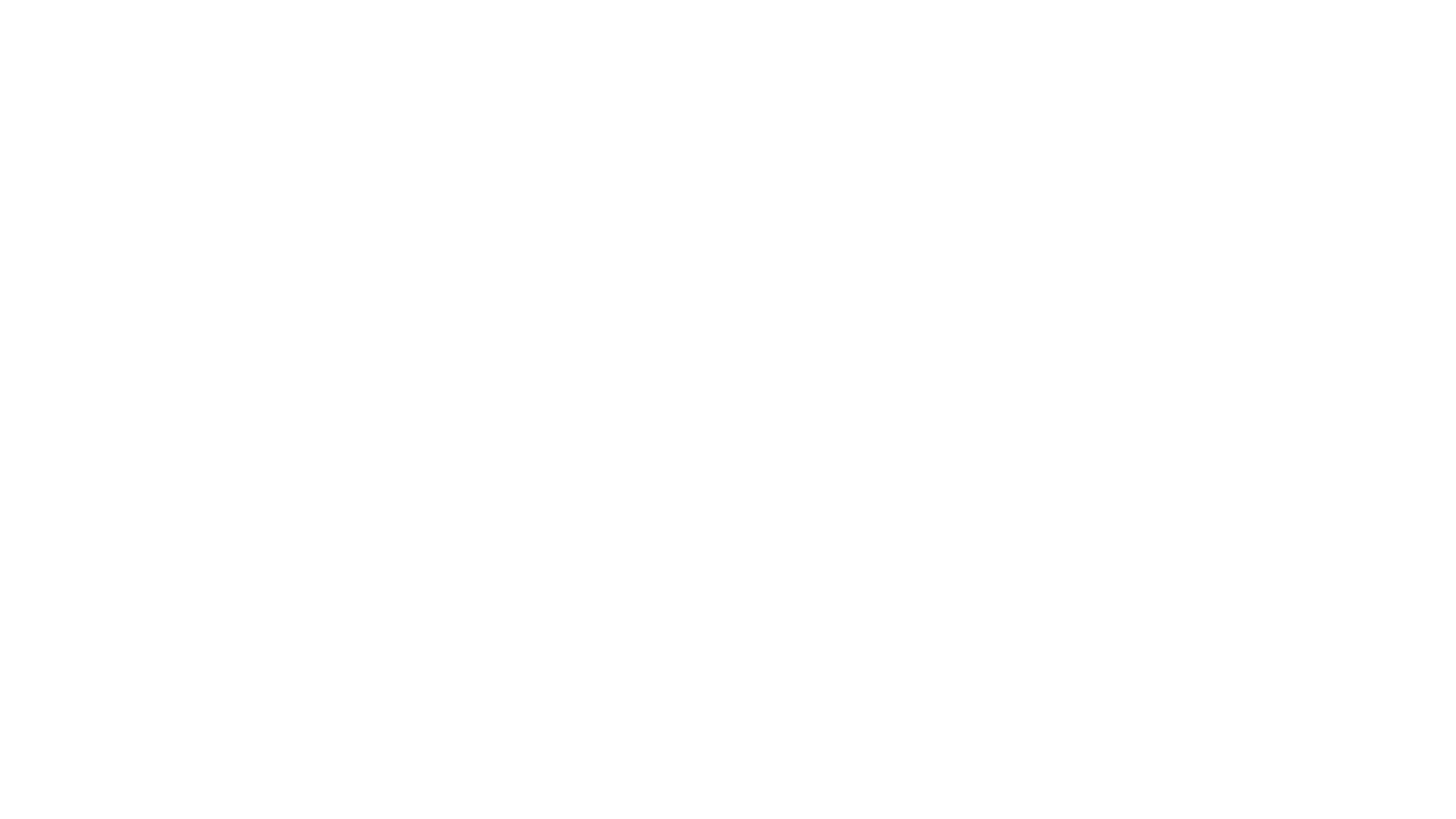
Credit: Photo by Rafli Firmansyah on Unsplash
Membawa perubahan sosial yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama aktivis maupun organisasi swadaya masyarakat, atau yang sekarang disebut organisasi masyarakat sipil. Perubahan sosial didorong melalui berbagai cara, termasuk aksi unjuk rasa di area publik yang disengaja atau tidak, akhirnya menjadi disruptif.
Memilih langkah untuk melakukan aksi unjuk rasa sangat manusiawi, karena aktivis acapkali didorong emosi marah melihat pelanggaran prinsip atau intuisi moral yang mereka pegang (ada alasannya kenapa sinonim protes atau demonstrasi adalah unjuk rasa). . Hal lain yang mungkin membuat aktivis memilih aksi protes karena dianggap sebagai sesuatu yang wajar dalam “perjuangan”, dibumbui dengan imaji heroik yang melekat terhadap sosok demonstran yang melawan penguasa.
Secara lebih strategis, langkah protes —apalagi yang ekstrem— sering diambil karena sudah banyak bukti, termasuk yang dikumpulkan secara ilmiah, yang menunjukkan kalau aksi ini berpotensi menarik perhatian media serta membuat publik dan penguasa sadar akan adanya sebuah masalah.
Namun, riset menunjukkan masyarakat malah tidak mendukung isu yang diusung aktivis lewat protes, jika aksinya mereka anggap menghambat kepentingan umum atau membahayakan banyak orang. Artinya, aktivis berhadapan dengan sebuah dilema: protes ekstrem sehingga menarik perhatian publik, tapi sekaligus juga akan menyurutkan dukungan masyarakat.
Memilih langkah untuk melakukan aksi unjuk rasa sangat manusiawi, karena aktivis acapkali didorong emosi marah melihat pelanggaran prinsip atau intuisi moral yang mereka pegang (ada alasannya kenapa sinonim protes atau demonstrasi adalah unjuk rasa). . Hal lain yang mungkin membuat aktivis memilih aksi protes karena dianggap sebagai sesuatu yang wajar dalam “perjuangan”, dibumbui dengan imaji heroik yang melekat terhadap sosok demonstran yang melawan penguasa.
Secara lebih strategis, langkah protes —apalagi yang ekstrem— sering diambil karena sudah banyak bukti, termasuk yang dikumpulkan secara ilmiah, yang menunjukkan kalau aksi ini berpotensi menarik perhatian media serta membuat publik dan penguasa sadar akan adanya sebuah masalah.
Namun, riset menunjukkan masyarakat malah tidak mendukung isu yang diusung aktivis lewat protes, jika aksinya mereka anggap menghambat kepentingan umum atau membahayakan banyak orang. Artinya, aktivis berhadapan dengan sebuah dilema: protes ekstrem sehingga menarik perhatian publik, tapi sekaligus juga akan menyurutkan dukungan masyarakat.
Banyak jalan untuk menyampaikan ide
Dalam menjalankan kampanye di ranah publik, aktivis atau organisasi masyarakat sipil memiliki beragam tujuan. Namun ,semuanya dapat digolongkan berdasarkan tujuan akhirnya: perubahan kebijakan atau perubahan perilaku sebagian kelompok masyarakat. Dalam tulisan ini, kita membahas yang pertama, kampanye publik untuk mendorong perubahan kebijakan.
Untuk mendorong perubahan kebijakan, aktivis sering melakukan advokasi (yang sebetulnya lebih pas disebut persuasi) kepada para pembuat kebijakan. Persuasi ini bisa terjadi dalam ruang tertutup melalui presentasi atau pertemuan privat, maupun di ruang terbuka melalui penyampaian pesan di ruang diskusi publik. Istilah “fraksi balkon” dalam sidang DPR yang membahas RUU merupakan satu bukti bahwa masukan organisasi masyarakat sipil sudah menjadi salah satu norma dalam pembuatan kebijakan. Contoh keberhasilan advokasi dapat ditemukan di berbagai tingkat di Indonesia, baik lokal maupun nasional. Yang terdekat mungkin adalah bagaimana upaya advokasi mengupayakan pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU-TPKS).
Selain advokasi kebijakan, aktivis juga sering melakukan kampanye di ranah publik untuk mengekspresikan kemarahan mereka dalam bentuk protes kepada pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab membuat masalah muncul atau bertahan. Kampanye dengan tujuan ini disebut sebagai kampanye ekspresi. Kampanye ekspresi juga bisa dipilih ketika aktivis merasa jalur advokasi sudah atau akan menemui kebuntuan alias sia-sia.
Salah satu pemeo populer saat ini adalah “semua berita adalah berita baik”. Dan memang sudah cukup banyak bukti empirisnya bahwa semakin ekstrem sebuah aksi, apapun konsekuensinya, maka akan semakin menarik perhatian media. Dengan sendirinya, aktivis sering percaya protes yang lebih dramatis —yang lalu disamakan dengan disruptif— lebih mungkin diliput media, sehingga lebih mungkin diketahui dan menarik simpati publik, dan akhirnya dapat mempengaruhi pembuat kebijakan.
Terbaca dalam paragraf sebelumnya bahwa seringkali aktivis yang berkampanye menggandeng atau bahkan menyamakan tujuan ekspresi dengan tujuan persuasi. Kampanye persuasi bertujuan mengajak masyarakat agar mau mendukung tuntutan yang diajukan aktivis atau organisasi yang berkampanye.
Jika tujuan protes murni hanya mengejar perhatian, langkah ini mungkin efektif, namun apakah aksi tersebut tepat untuk mendulang dukungan warga?
Untuk mendorong perubahan kebijakan, aktivis sering melakukan advokasi (yang sebetulnya lebih pas disebut persuasi) kepada para pembuat kebijakan. Persuasi ini bisa terjadi dalam ruang tertutup melalui presentasi atau pertemuan privat, maupun di ruang terbuka melalui penyampaian pesan di ruang diskusi publik. Istilah “fraksi balkon” dalam sidang DPR yang membahas RUU merupakan satu bukti bahwa masukan organisasi masyarakat sipil sudah menjadi salah satu norma dalam pembuatan kebijakan. Contoh keberhasilan advokasi dapat ditemukan di berbagai tingkat di Indonesia, baik lokal maupun nasional. Yang terdekat mungkin adalah bagaimana upaya advokasi mengupayakan pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU-TPKS).
Selain advokasi kebijakan, aktivis juga sering melakukan kampanye di ranah publik untuk mengekspresikan kemarahan mereka dalam bentuk protes kepada pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab membuat masalah muncul atau bertahan. Kampanye dengan tujuan ini disebut sebagai kampanye ekspresi. Kampanye ekspresi juga bisa dipilih ketika aktivis merasa jalur advokasi sudah atau akan menemui kebuntuan alias sia-sia.
Salah satu pemeo populer saat ini adalah “semua berita adalah berita baik”. Dan memang sudah cukup banyak bukti empirisnya bahwa semakin ekstrem sebuah aksi, apapun konsekuensinya, maka akan semakin menarik perhatian media. Dengan sendirinya, aktivis sering percaya protes yang lebih dramatis —yang lalu disamakan dengan disruptif— lebih mungkin diliput media, sehingga lebih mungkin diketahui dan menarik simpati publik, dan akhirnya dapat mempengaruhi pembuat kebijakan.
Terbaca dalam paragraf sebelumnya bahwa seringkali aktivis yang berkampanye menggandeng atau bahkan menyamakan tujuan ekspresi dengan tujuan persuasi. Kampanye persuasi bertujuan mengajak masyarakat agar mau mendukung tuntutan yang diajukan aktivis atau organisasi yang berkampanye.
Jika tujuan protes murni hanya mengejar perhatian, langkah ini mungkin efektif, namun apakah aksi tersebut tepat untuk mendulang dukungan warga?
Dilema aktivis dalam menjalankan kampanye
Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan di Journal of Personality and Social Psychology tahun 2020, tiga orang peneliti dari Stanford University dan University of Toronto menemukan bahwa publik malah cenderung enggan mendukung isu yang diusung atau aktivis yang mengusungnya jika mereka mempersepsikan protes dilaksanakan secara disruptif atau membahayakan.
Temuan ini merupakan hasil dari enam eksperimen yang mengeksplorasi reaksi terhadap beragam aksi protes disruptif dalam berbagai gerakan sosial, baik dalam agenda progresif (misalnya: oposisi terhadap pencalonan presiden Donald Trump) maupun konservatif (misalnya: gerakan anti aborsi). Sebagian responden (masuk dalam kelompok eksperimen) membaca tulisan yang mendeskripsikan aksi protes yang mengganggu kepentingan umum atau membahayakan orang lain (misalnya menyandera polisi). Sebagian lainnya (masuk dalam kelompok kontrol) membaca tulisan yang mendeskripsikan aksi protes yang lebih netral (misalnya memboikot produk sebuah perusahaan). Semua responden ditanya sejauh mana mereka mendukung isu yang diusung dan aktivis yang melakukan aksi. Ternyata, keenam eksperimen itu menunjukkan hasil yang konsisten: responden yang membaca aksi protes yang ekstrem lebih kecil dukungannya ke isu maupun aktivis pelaku unjuk rasa, dibandingkan responden yang membaca aksi protes yang netral. Hasil ini konsisten dan tidak dipengaruhi ideologi responden (liberal atau konservatif). Misalnya, bahkan kaum liberal garis keras pun menunjukkan dukungan yang lebih sedikit terhadap gerakan anti-Trump setelah mebaca tentang aksi protes ekstrem melawan Trump.
Mengapa ini bisa terjadi? Mekanismenya dapat diilustrasikan melalui diagram di bawah ini. Jika seseorang menilai aksi protes mengganggu kepentingan umum atau membahayakan orang lain, maka orang itu akan menilai bahwa aksi ini imoral. Persepsi imoralitas ini memangkas hubungan emosional dengan isu yang diusung, dan identifikasi dengan si aktivis. Akibatnya, orang itu akan mengurangi kesediannya untuk mendukung atau bergabung dengan gerakan sosial di balik protes itu.
Temuan ini merupakan hasil dari enam eksperimen yang mengeksplorasi reaksi terhadap beragam aksi protes disruptif dalam berbagai gerakan sosial, baik dalam agenda progresif (misalnya: oposisi terhadap pencalonan presiden Donald Trump) maupun konservatif (misalnya: gerakan anti aborsi). Sebagian responden (masuk dalam kelompok eksperimen) membaca tulisan yang mendeskripsikan aksi protes yang mengganggu kepentingan umum atau membahayakan orang lain (misalnya menyandera polisi). Sebagian lainnya (masuk dalam kelompok kontrol) membaca tulisan yang mendeskripsikan aksi protes yang lebih netral (misalnya memboikot produk sebuah perusahaan). Semua responden ditanya sejauh mana mereka mendukung isu yang diusung dan aktivis yang melakukan aksi. Ternyata, keenam eksperimen itu menunjukkan hasil yang konsisten: responden yang membaca aksi protes yang ekstrem lebih kecil dukungannya ke isu maupun aktivis pelaku unjuk rasa, dibandingkan responden yang membaca aksi protes yang netral. Hasil ini konsisten dan tidak dipengaruhi ideologi responden (liberal atau konservatif). Misalnya, bahkan kaum liberal garis keras pun menunjukkan dukungan yang lebih sedikit terhadap gerakan anti-Trump setelah mebaca tentang aksi protes ekstrem melawan Trump.
Mengapa ini bisa terjadi? Mekanismenya dapat diilustrasikan melalui diagram di bawah ini. Jika seseorang menilai aksi protes mengganggu kepentingan umum atau membahayakan orang lain, maka orang itu akan menilai bahwa aksi ini imoral. Persepsi imoralitas ini memangkas hubungan emosional dengan isu yang diusung, dan identifikasi dengan si aktivis. Akibatnya, orang itu akan mengurangi kesediannya untuk mendukung atau bergabung dengan gerakan sosial di balik protes itu.
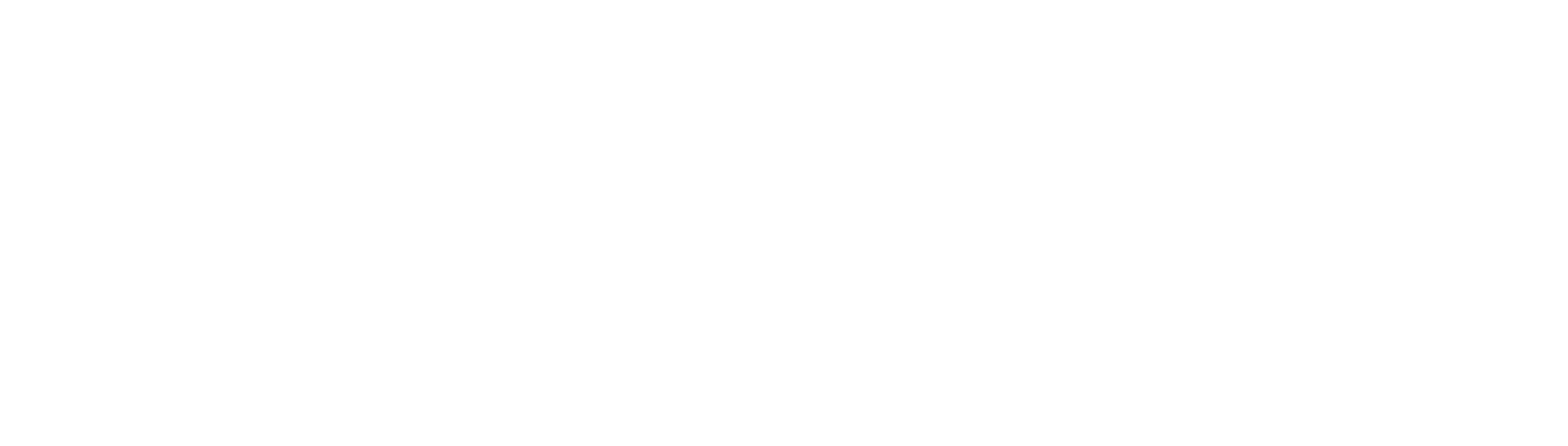
Jika kita hanya melihat penelitian ini, mungkin ada kesan bahwa gerakan sosial seharusnya tidak pernah menggunakan protes yang keras. Namun, penelitian tahun 2015 mengenai protes di masa segregasi A.S. dan protes menuntut hak pilih buat perempuan di Inggris di awal abad 20, menunjukkan bahwa tetap ada dampak dari aksi protes yang disruptif. Selain itu, aksi protes disruptif terbukti bermanfaat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat awam mengenai keberadaan suatu gerakan.
Aktivis lantas menghadapi sebuah dilema: perlukah mereka memberikan tekanan secara disruptif untuk menarik perhatian serta liputan media, dengan risiko mengurangi dukungan masyarakat? Bagaimana dengan sebaliknya?
Aktivis lantas menghadapi sebuah dilema: perlukah mereka memberikan tekanan secara disruptif untuk menarik perhatian serta liputan media, dengan risiko mengurangi dukungan masyarakat? Bagaimana dengan sebaliknya?
Perlu bagi-bagi tugas untuk mengepung dari segala arah
Lalu bagaimana cara memecahkan dilema ini? Menurut kami, ada jalan tengah yang bisa diambil. Protes yang ekspresif tetap perlu dilakukan, karena liputan media bisa membuat lebih banyak warga yang akhirnya paham ada situasi yang harus diubah. Namun protes ekspresif harus selalu didampingi kampanye persuasi menggalang dukungan publik sekaligus advokasi kebijakan —jika jalurnya memang memungkinkan.
Tidak berarti tiga hal ini harus dilakukan berbarengan oleh satu organisasi. Sebaliknya, bagi-bagi tugas sangat penting karena mereka yang “kebagian” peran untuk jadi juru protes kemungkinan besar tidak akan pernah diundang masukannya oleh penguasa. Selain itu, organisasi yang berperan mengajak warga mendukung agenda perubahan tidak bisa melakukan aksi ekstrem kalau mau efektif. Bagi-bagi tugas akan “mengepung” isu dari semua sisi dan membuat kesempatan akan adanya perubahan semakin besar.
Ketika kita bicara persuasi, sasaran utamanya adalah masyarakat awam yang tidak (atau kita harap, belum) sepeduli aktivis tentang isu. Ketidakpedulian ini bisa jadi ada karena belum paham, tidak merasa perlu paham, atau tidak ada alasan yang memaksa mereka untuk paham. Pendekatan lain yang bisa kita lakukan adalah kampanye yang persuasif dan tidak menggurui. Ini akan sangat efektif untuk menghindari resistensi dari bagian masyarakat yang cenderung apatis terhadap perubahan.
Untuk orang-orang ini, kita bisa menggunakan modus komunikasi "interupsi" di saat kita menjangkau mereka untuk pertama kalinya. Modus komunikasi “interupsi” berfungsi seperti iklan produk komersial, di mana publik yang belum pernah menerima eksposur isu ini “dibuat terpapar” di ruang publik.
Meskipun demikian, jangan juga berharap bahwa mereka yang tadinya tak peduli langsung mau terlibat penuh. Tidak ada solusi instan untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian. Kunci dari semua ini adalah komunikasi yang konsisten dan berkelanjutan.
Sejalan dengan ini, ketika warga yang awalnya peduli sudah terlihat mau lebih terlibat, para aktivis di organisasi masyarakat sipil harus sudah siap menampung dan menyalurkan energi mereka dengan menyediakan berbagai pilihan bentuk keterlibatan, mulai dari yang “kelas ringan” seperti menyebarkan konten atau menandatangani petisi, “kelas welter” seperti berdonasi uang atau waktu, sampai “kelas berat” seperti ikut aksi unjuk rasa. Jangan sampai momentum yang sudah dibangun dengan susah payah hilang.
Pada akhirnya, kunci untuk memecah dilema ini adalah koordinasi pendorong perubahan yang menjalankan protes, persuasi, dan advokasi di lini masing-masing.
Tidak berarti tiga hal ini harus dilakukan berbarengan oleh satu organisasi. Sebaliknya, bagi-bagi tugas sangat penting karena mereka yang “kebagian” peran untuk jadi juru protes kemungkinan besar tidak akan pernah diundang masukannya oleh penguasa. Selain itu, organisasi yang berperan mengajak warga mendukung agenda perubahan tidak bisa melakukan aksi ekstrem kalau mau efektif. Bagi-bagi tugas akan “mengepung” isu dari semua sisi dan membuat kesempatan akan adanya perubahan semakin besar.
Ketika kita bicara persuasi, sasaran utamanya adalah masyarakat awam yang tidak (atau kita harap, belum) sepeduli aktivis tentang isu. Ketidakpedulian ini bisa jadi ada karena belum paham, tidak merasa perlu paham, atau tidak ada alasan yang memaksa mereka untuk paham. Pendekatan lain yang bisa kita lakukan adalah kampanye yang persuasif dan tidak menggurui. Ini akan sangat efektif untuk menghindari resistensi dari bagian masyarakat yang cenderung apatis terhadap perubahan.
Untuk orang-orang ini, kita bisa menggunakan modus komunikasi "interupsi" di saat kita menjangkau mereka untuk pertama kalinya. Modus komunikasi “interupsi” berfungsi seperti iklan produk komersial, di mana publik yang belum pernah menerima eksposur isu ini “dibuat terpapar” di ruang publik.
Meskipun demikian, jangan juga berharap bahwa mereka yang tadinya tak peduli langsung mau terlibat penuh. Tidak ada solusi instan untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian. Kunci dari semua ini adalah komunikasi yang konsisten dan berkelanjutan.
Sejalan dengan ini, ketika warga yang awalnya peduli sudah terlihat mau lebih terlibat, para aktivis di organisasi masyarakat sipil harus sudah siap menampung dan menyalurkan energi mereka dengan menyediakan berbagai pilihan bentuk keterlibatan, mulai dari yang “kelas ringan” seperti menyebarkan konten atau menandatangani petisi, “kelas welter” seperti berdonasi uang atau waktu, sampai “kelas berat” seperti ikut aksi unjuk rasa. Jangan sampai momentum yang sudah dibangun dengan susah payah hilang.
Pada akhirnya, kunci untuk memecah dilema ini adalah koordinasi pendorong perubahan yang menjalankan protes, persuasi, dan advokasi di lini masing-masing.
Referensi
- Feinberg, M., Willer, R., & Kovacheff, C. (2020). The activist’s dilemma: Extreme protest actions reduce popular support for social movements. Journal of Personality and Social Psychology, 119(5), 1086–1111. https://doi.org/10.1037/pspi0000230
- Biggs, M., & Andrews, K. (2015). Protest Campaigns and Movement Success. American Sociological Review, 80(2), 416-443.
Related Articles