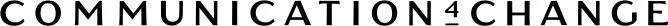Kesalahan-kesalahan umum dalam komunikasi publik organisasi masyarakat sipil
By Paramita Mohamad
March 6, 2018
March 6, 2018

Kucing yang tidur telentang adalah kucing yang percaya dengan lingkungan sekitarnya.
Tentu ada beragam alasan dan agenda yang membawa Anda ke dalam organisasi masyarakat sipil. Namun saya yakin bahwa semuanya bermuara ke satu tujuan: Anda ingin ikut membenahi Indonesia.
Draf Dokumen Rencana Strategis International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) tahun 2018–2021 mengakui pentingnya komunikasi publik untuk membantu kerja dan memupuk kredibilitas organisasi masyarakat sipil. Getolnya masyarakat Indonesia menggunakan media sosial dan populernya petisi daring (online) mungkin membuat Anda optimistis bahwa komunikasi publik efektif untuk mengakselerasi perubahan. Barangkali Anda juga mendengar beberapa kasus “kemenangan” dari petisi-petisi ini. Selain itu, hati Anda mungkin mekar menyaksikan perubahan terjadi di beberapa area yang akhirnya ramai di media sosial dan digiring dalam petisi daring, misalnya pembatalan peraturan menteri dalam negeri tentang penelitian, dan penundaan pengesahan RKUHP kemarin.
Dalam ilmu perilaku ada fenomena yang disebut survivor bias atau bias penyintas: kita cenderung hanya melihat contoh-contoh keberhasilan, dan buta pada contoh kegagalan yang sebetulnya jauh lebih banyak. Nampaknya kita mengalami bias penyintas dalam melihat efektivitas komunikasi publik lewat media sosial. Hasil penelusuran petisi di situs change.org dengan kata kunci “Indonesia” mendapatkan 2.065 petisi yang termuat dalam 207 laman. Namun dalam beberapa klik saja kita bisa melihat bahwa petisi yang dinyatakan “menang” di Indonesia hanya termuat dalam 7 laman. Komunikasi publik masyarakat sipil melalui media sosial dan petisi daring tidak selalu ampuh mempercepat datangnya perubahan.
Saya tidak bermaksud meredam optimisme Anda terhadap potensi komunikasi publik. Saya percaya komunikasi publik dari organisasi masyarakat sipil bisa mengakselerasi perubahan. Namun justru praktik di dalam organisasi masyarakat sipil sendiri yang menumpulkan daya katalis komunikasi publik.
Memperlakukan komunikasi publik sebagai anak bawang
Sejak mendirikan Communication for Change di tahun 2016, mayoritas klien saya adalah institusi nirlaba. Saya mengamati bahwa organisasi masyarakat sipil umumnya memperlakukan komunikasi publik sebagai anak bawang (walau belum sampai seperti anak tiri). Anak bawang dalam KBBI artinya adalah “peserta bermain yang tidak masuk hitungan (hanya sebagai penggenap atau ikut-ikutan saja)”. Upaya komunikasi publik sering diperlakukan sebagai penggenap yang datang belakangan. Istilah dalam bahasa Inggrisnya adalah “an afterthought”, dan mungkin terjemahan yang paling pas dalam bahasa kita adalah embel-embel.
Ini adalah ciri-ciri dari diperlakukannya komunikasi publik sebagai anak bawang dalam organisasi masyarakat sipil:
Saya juga melihat bahwa banyak organisasi masyarakat sipil seakan memisahkan antara komunikasi (yang berputar di publikasi kegiatan) dengan kegiatan yang diberi label sosialiasi, mobilisasi, atau penjangkauan. Tidakkah ketiga hal tersebut pada hakekatnya adalah komunikasi juga? Mungkinkah karena sosialisasi dan teman-temannya itu adalah bagian dari advokasi, sementara komunikasi diartikan sebagai publikasi?
Tujuan akhir dari komunikasi institusi nirlaba, apapun organisasinya, ada dua:
Bagaimana dengan perubahan opini publik? Perubahan opini publik adalah tujuan antara. Terkadang kita harus mengubah sentimen masyarakat dulu sehingga kebijakan akhirnya bisa berubah (misalnya civil rights movement di Amerika Serikat). Dalam disiplin kesehatan masyarakat, sikap dan perasaan suatu kelompok masyarakat seringkali perlu diubah dulu agar kebiasaannya berubah (misalnya membawa rompi darurat di mobil di Prancis).
Melihat dua tujuan akhir di atas, maka saya tidak melihat pentingnya mempertanyakan apa saja yang masuk advokasi, dan apa saja bagian komunikasi. Untuk memulai suatu upaya komunikasi publik dalam rangka mengubah kebijakan, maka pertanyaan yang lebih produktif adalah:
Draf Dokumen Rencana Strategis International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) tahun 2018–2021 mengakui pentingnya komunikasi publik untuk membantu kerja dan memupuk kredibilitas organisasi masyarakat sipil. Getolnya masyarakat Indonesia menggunakan media sosial dan populernya petisi daring (online) mungkin membuat Anda optimistis bahwa komunikasi publik efektif untuk mengakselerasi perubahan. Barangkali Anda juga mendengar beberapa kasus “kemenangan” dari petisi-petisi ini. Selain itu, hati Anda mungkin mekar menyaksikan perubahan terjadi di beberapa area yang akhirnya ramai di media sosial dan digiring dalam petisi daring, misalnya pembatalan peraturan menteri dalam negeri tentang penelitian, dan penundaan pengesahan RKUHP kemarin.
Dalam ilmu perilaku ada fenomena yang disebut survivor bias atau bias penyintas: kita cenderung hanya melihat contoh-contoh keberhasilan, dan buta pada contoh kegagalan yang sebetulnya jauh lebih banyak. Nampaknya kita mengalami bias penyintas dalam melihat efektivitas komunikasi publik lewat media sosial. Hasil penelusuran petisi di situs change.org dengan kata kunci “Indonesia” mendapatkan 2.065 petisi yang termuat dalam 207 laman. Namun dalam beberapa klik saja kita bisa melihat bahwa petisi yang dinyatakan “menang” di Indonesia hanya termuat dalam 7 laman. Komunikasi publik masyarakat sipil melalui media sosial dan petisi daring tidak selalu ampuh mempercepat datangnya perubahan.
Saya tidak bermaksud meredam optimisme Anda terhadap potensi komunikasi publik. Saya percaya komunikasi publik dari organisasi masyarakat sipil bisa mengakselerasi perubahan. Namun justru praktik di dalam organisasi masyarakat sipil sendiri yang menumpulkan daya katalis komunikasi publik.
Memperlakukan komunikasi publik sebagai anak bawang
Sejak mendirikan Communication for Change di tahun 2016, mayoritas klien saya adalah institusi nirlaba. Saya mengamati bahwa organisasi masyarakat sipil umumnya memperlakukan komunikasi publik sebagai anak bawang (walau belum sampai seperti anak tiri). Anak bawang dalam KBBI artinya adalah “peserta bermain yang tidak masuk hitungan (hanya sebagai penggenap atau ikut-ikutan saja)”. Upaya komunikasi publik sering diperlakukan sebagai penggenap yang datang belakangan. Istilah dalam bahasa Inggrisnya adalah “an afterthought”, dan mungkin terjemahan yang paling pas dalam bahasa kita adalah embel-embel.
Ini adalah ciri-ciri dari diperlakukannya komunikasi publik sebagai anak bawang dalam organisasi masyarakat sipil:
- Tidak ada investasi serius dalam tenaga dan waktu untuk merancang strategi komunikasi sebelum melakukan implementasi; tidak ada yang memikirkan secara mendalam keterkaitan antara misi organisasi, tujuan program, dan aspek-aspek dalam komunikasi yang terjadi di ruang publik
- Kalaupun komunikasi sempat dibahas saat membuat desain merancang strategi program, ia hanya disebut sebagai salah satu butir dalam seluruh rangkaian aktivitas
- Komunikasi baru mulai dipikirkan setelah aktivitas akan berlangsung (karena harus membuat poster undangan di media sosial, membuat siaran ke media, atau melakukan live-tweet saat acara)
- Secara otomatis tanpa pertimbangan selalu memilih produk komunikasi yang itu-itu saja
- Tidak adanya call-to-action (seruan aksi) yang jelas dalam komunikasi publik yang bertujuan untuk menggalang aksi.
Saya juga melihat bahwa banyak organisasi masyarakat sipil seakan memisahkan antara komunikasi (yang berputar di publikasi kegiatan) dengan kegiatan yang diberi label sosialiasi, mobilisasi, atau penjangkauan. Tidakkah ketiga hal tersebut pada hakekatnya adalah komunikasi juga? Mungkinkah karena sosialisasi dan teman-temannya itu adalah bagian dari advokasi, sementara komunikasi diartikan sebagai publikasi?
Tujuan akhir dari komunikasi institusi nirlaba, apapun organisasinya, ada dua:
- Perubahan kebijakan
- Perubahan tingkah laku sosial
Bagaimana dengan perubahan opini publik? Perubahan opini publik adalah tujuan antara. Terkadang kita harus mengubah sentimen masyarakat dulu sehingga kebijakan akhirnya bisa berubah (misalnya civil rights movement di Amerika Serikat). Dalam disiplin kesehatan masyarakat, sikap dan perasaan suatu kelompok masyarakat seringkali perlu diubah dulu agar kebiasaannya berubah (misalnya membawa rompi darurat di mobil di Prancis).
Melihat dua tujuan akhir di atas, maka saya tidak melihat pentingnya mempertanyakan apa saja yang masuk advokasi, dan apa saja bagian komunikasi. Untuk memulai suatu upaya komunikasi publik dalam rangka mengubah kebijakan, maka pertanyaan yang lebih produktif adalah:
Siapakah yang membuat kebijakan itu? Siapa yang memengaruhi si pembuat kebijakan? Dalam konteks apa saja mereka bersinggungan dengannya? Bagaimana komunikasi yang berlangsung terbuka di ruang publik bisa memicu perubahan dalam pikiran, perasaan, dan perilaku si pembuat kebijakan dan orang-orang yang memengaruhinya?
Sementara untuk memulai suatu upaya komunikasi publik dalam rangka mengubah perilaku suatu kelompok, maka pertanyaan yang lebih produktif adalah:
Siapakah yang melakukan perilaku tersebut? Apa dan siapa saja yang mendorong mereka untuk mulai melakukannya? Apa dan siapa saja yang mendorong mereka untuk terus melakukannya? Apa yang menghalangi mereka untuk memulai perilaku yang baru? Apa yang harus berubah dalam kepercayaan dan perasaan mereka? Apa yang harus berubah dalam kepercayaan dan perasaan dari pihak-pihak yang memengaruhi mereka? Bagaimana komunikasi yang terjadi di ruang publik bisa memicu perubahan-perubahan itu?
Jika Anda mencurigai bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut juga diajukan pada saat merancang strategi program, Anda benar. Pertanyaan-pertanyaan untuk mendesain komunikasi di ruang publik adalah pertanyaan-pertanyaan tentang strategi program.
Artinya, organisasi masyarakat sipil harus berhenti memperlakukan komunikasi publik sebagai kegiatan pelengkap alias embel-embel. Komunikasi publik hanya bisa efektif mempercepat perubahan jika dirancang dengan seksama saat kita membuat strategi program. Dengan kata lain, strategi komunikasi publik adalah bagian tak terpisahkan dari strategi program organisasi.
Merancang strategi dengan modus “yang penting ada”
Sebagai konsekuensi dari langkah pertama, maka langkah selanjutnya adalah organisasi harus lebih serius menginvestasikan waktu dan tenaga dalam merancang strategi komunikasi publik.
Strategi adalah praktik menentukan cara terbaik menuju ke sana (tujuan) dari sini (titik awal). Pada hakekatnya, menyusun sebuah strategi adalah sama dengan menyusun sebuah argumen mengenai pendekatan mana yang paling tepat untuk mengatasi penghalang antara sini dan sana. Argumen ini tentu harus dibangun dengan premis-premis yang faktual, dari data yang akurat, dan asumsi yang realistis. Selain itu, premis-premis ini pun harus terikat dalam satu logika yang lempeng.
Sebagai sebuah argumen, strategi harus memiliki elemen-elemen berikut:
Seringkali dokumen yang diberi judul “strategi” melewati dua elemen penting yang sebetulnya adalah jantung dari sebuah strategi, yakni hipotesis tentang akar masalah dan pendekatan apa yang dipilih untuk mengatasi halangan tersebut. Padahal tanpa dua elemen ini, yang kita punya hanyalah to-do list tanpa fokus, logika, dan implikasi pada alokasi sumber daya.
Strategi menuntut fokus, dan seringkali kita lupa bahwa fokus berarti pengorbanan. Dalam strategi, apa yang tidak akan kita lakukan sama pentingnya dengan apa yang akan kita lakukan. Tanpa hipotesis tentang akar masalah dan pendekatan yang dipilih untuk mengatasinya, kita tidak punya dasar yang kuat untuk menentukan apa yang akan kita korbankan.
Dalam strategi komunikasi yang baik, change statement selalu dirumuskan dari sudut pandang sasaran komunikasi. Ada beberapa kesalahan yang sering saya amati dalam komunikasi publik organisasi masyarakat sipil dalam hal ini:
Pertama, gagal mendefinisikan dengan tegas siapa yang harusnya menjadi sasaran komunikasi. Sebutan seperti “masyarakat setempat” atau “masyarakat awam” tidak cukup. Gunakan deskripsi yang lebih detail, misalnya “warga kabupaten yang tadinya tidak memilih si bupati dalam pilkada kemarin, yang harus diyakinkan untuk menyumbangkan suara ke bupati ini agar bisa dipilih kembali”, atau “orang tua suami yang masih menganggap bahwa jika istri bekerja, maka suami turun derajatnya”.
Kedua, menggunakan satu output komunikasi untuk menyasar lebih dari satu kelompok sasaran. Jika kita melakukan hal ini, maka pesan dalam output itu menjadi kabur.
Ketiga, beranjak dari asumsi bahwa kelompok sasaran sama pedulinya dengan kita tentang isyu yang kita kawal. Sebagai organisasi yang mengawal isyu ini tentu Anda percaya bahwa ini penting untuk memperbaiki Indonesia, dan semakin banyak orang yang “melek” isyu ini, makin lancar jalan menuju Indonesia yang lebih baik.
Mungkin karena itu saya sering menemukan kata-kata seperti “mencerahkan”, “menyadarkan”, dan “mengedukasi” tersirat sebagai change statement dalam strategi komunikasi publik. Padahal masyarakat umum, apalagi yang tidak terlibat langsung dalam isyu ini, punya banyak hal yang lebih mendesak yang menjejali pikiran dan menguras perasaannya.
Saya yakin komunikasi publik akan lebih efektif jika dimulai dengan asumsi bahwa sasaran kita mungkin tidak peduli, dan itu bukan salah mereka. Saya sendiri selalu mulai dengan posisi default bahwa kelompok sasaran adalah indifference (mungkin terjemahannya adalah acuh tak acuh). Konsekuensinya, saya selalu berpikir bahwa dalam banyak hal, komunikasi adalah upaya melawan rasa acuh tak acuh (fighting indifference). Memandang komunikasi publik lebih mirip sebagai bujuk rayu dan bukan pencerahan akan membawa saya pada strategi dan eksekusi yang lebih ampuh mendatangkan perubahan.
Enggan bekerja dengan praktisi profesional
Komunikasi adalah masalah stimulus dan respons. Respons adalah semua impresi yang muncul dalam pikiran atau perasaan orang-orang tentang suatu hal — dalam hal ini, isyu yang kita usung. Stimulus adalah segala elemen sensoris dan pengalaman, baik yang sengaja dirancang atau tidak, baik datang langsung atau melalui orang lain, yang bisa menimbulkan berbagai respons tersebut.
Strategi berkaitan dengan menentukan respons yang tepat di orang yang tepat, melalui cara dan media yang tepat, dalam waktu yang tepat. Strategi adalah urusan logika (logic). Sementara kreativitas dan imajinasi dibutuhkan untuk menyusun stimulus yang bisa menggugah dan mengalahkan ketidakpedulian. Ini adalah magic yang melampaui logika.
Saya percaya bahwa peradaban maju antara lain karena ada spesialisasi, pembagian tugas, dan pertukaran sukarela antara para spesialis. Demikian pula halnya untuk membuat magic dari komunikasi publik organisasi masyarakat sipil. Apalagi saat ini, sudah banyak pekerja kreatif berkualitas yang bekerja mandiri. Platform atau marketplace yang mempertemukan antara pengguna jasa dan mereka pun sudah banyak di Indonesia, seperti FIverr, Upwork, Freelance.com, Projects.co.id, Sribulancer, dan Behance. Belum pernah organisasi masyarakat sipil punya pilihan sebanyak ini untuk menemukan praktisi profesional yang sesuai dengan anggaran dan kebutuhan, seperti saat ini.
Organisasi masyarakat sipil bisa mempunyai hubungan kerja yang produktif dengan praktisi profesional asalkan dari awal sudah memberi arahan (brief) yang jelas dan tidak berubah-ubah di tengah jalan. Seringkali dengan arahan yang baik, praktisi profesional akan tertantang atau terdorong untuk melibatkan diri dalam isyu ini. Dalam proses pembuatan output komunikasi, organisasi masyarakat sipil memberi umpan balik yang spesifik dan bertolak dari arahan, bukan dari selera dan asumsi pribadi. Dan tentu saja, ini semua percuma tanpa pembayaran dan proses yang transparan dan adil.
Kami mempunyai blanko arahan buat pekerja kreatif profesional yang bisa Anda gunakan. Jika Anda memerlukannya, Anda bisa meninggalkan pesan di situs kami. Namun Anda harus sudah mempunyai strategi komunikasi yang tajam dan lengkap untuk bisa mengisi blanko itu dengan baik.
Kesimpulannya: jika ingin lebih sering melakukan komunikasi publik yang ampuh mengakselerasi perubahan, organisasi masyarakat sipil mempunyai tiga pekerjaan rumah utama. Pertama, berhenti memperlakukan komunikasi publik sebagai anak bawang; kedua, mulai berinvestasi lebih serius untuk menyusun strategi komunikasi bersamaan dengan strategi program; dan terakhir, mulai mencoba untuk bekerja dengan praktisi profesional.
Godspeed, rebels.
Artinya, organisasi masyarakat sipil harus berhenti memperlakukan komunikasi publik sebagai kegiatan pelengkap alias embel-embel. Komunikasi publik hanya bisa efektif mempercepat perubahan jika dirancang dengan seksama saat kita membuat strategi program. Dengan kata lain, strategi komunikasi publik adalah bagian tak terpisahkan dari strategi program organisasi.
Merancang strategi dengan modus “yang penting ada”
Sebagai konsekuensi dari langkah pertama, maka langkah selanjutnya adalah organisasi harus lebih serius menginvestasikan waktu dan tenaga dalam merancang strategi komunikasi publik.
Strategi adalah praktik menentukan cara terbaik menuju ke sana (tujuan) dari sini (titik awal). Pada hakekatnya, menyusun sebuah strategi adalah sama dengan menyusun sebuah argumen mengenai pendekatan mana yang paling tepat untuk mengatasi penghalang antara sini dan sana. Argumen ini tentu harus dibangun dengan premis-premis yang faktual, dari data yang akurat, dan asumsi yang realistis. Selain itu, premis-premis ini pun harus terikat dalam satu logika yang lempeng.
Sebagai sebuah argumen, strategi harus memiliki elemen-elemen berikut:
- Deskripsi tentang di mana kita sekarang (titik awal)
- Deskripsi tentang ke mana kita ingin sampai (titik akhir)
- Apa yang menjadi penghalang antara titik awal dan titik akhir (what stands in between)
- Pendekatan apa yang kita pilih untuk mencapai titik akhir (the chosen approach, the guiding policy; dalam strategi komunikasi elemen ini disebut sebagai change statement)
- Rangkaian langkah yang harus diambil (the course of action).
Seringkali dokumen yang diberi judul “strategi” melewati dua elemen penting yang sebetulnya adalah jantung dari sebuah strategi, yakni hipotesis tentang akar masalah dan pendekatan apa yang dipilih untuk mengatasi halangan tersebut. Padahal tanpa dua elemen ini, yang kita punya hanyalah to-do list tanpa fokus, logika, dan implikasi pada alokasi sumber daya.
Strategi menuntut fokus, dan seringkali kita lupa bahwa fokus berarti pengorbanan. Dalam strategi, apa yang tidak akan kita lakukan sama pentingnya dengan apa yang akan kita lakukan. Tanpa hipotesis tentang akar masalah dan pendekatan yang dipilih untuk mengatasinya, kita tidak punya dasar yang kuat untuk menentukan apa yang akan kita korbankan.
Dalam strategi komunikasi yang baik, change statement selalu dirumuskan dari sudut pandang sasaran komunikasi. Ada beberapa kesalahan yang sering saya amati dalam komunikasi publik organisasi masyarakat sipil dalam hal ini:
Pertama, gagal mendefinisikan dengan tegas siapa yang harusnya menjadi sasaran komunikasi. Sebutan seperti “masyarakat setempat” atau “masyarakat awam” tidak cukup. Gunakan deskripsi yang lebih detail, misalnya “warga kabupaten yang tadinya tidak memilih si bupati dalam pilkada kemarin, yang harus diyakinkan untuk menyumbangkan suara ke bupati ini agar bisa dipilih kembali”, atau “orang tua suami yang masih menganggap bahwa jika istri bekerja, maka suami turun derajatnya”.
Kedua, menggunakan satu output komunikasi untuk menyasar lebih dari satu kelompok sasaran. Jika kita melakukan hal ini, maka pesan dalam output itu menjadi kabur.
Ketiga, beranjak dari asumsi bahwa kelompok sasaran sama pedulinya dengan kita tentang isyu yang kita kawal. Sebagai organisasi yang mengawal isyu ini tentu Anda percaya bahwa ini penting untuk memperbaiki Indonesia, dan semakin banyak orang yang “melek” isyu ini, makin lancar jalan menuju Indonesia yang lebih baik.
Mungkin karena itu saya sering menemukan kata-kata seperti “mencerahkan”, “menyadarkan”, dan “mengedukasi” tersirat sebagai change statement dalam strategi komunikasi publik. Padahal masyarakat umum, apalagi yang tidak terlibat langsung dalam isyu ini, punya banyak hal yang lebih mendesak yang menjejali pikiran dan menguras perasaannya.
Saya yakin komunikasi publik akan lebih efektif jika dimulai dengan asumsi bahwa sasaran kita mungkin tidak peduli, dan itu bukan salah mereka. Saya sendiri selalu mulai dengan posisi default bahwa kelompok sasaran adalah indifference (mungkin terjemahannya adalah acuh tak acuh). Konsekuensinya, saya selalu berpikir bahwa dalam banyak hal, komunikasi adalah upaya melawan rasa acuh tak acuh (fighting indifference). Memandang komunikasi publik lebih mirip sebagai bujuk rayu dan bukan pencerahan akan membawa saya pada strategi dan eksekusi yang lebih ampuh mendatangkan perubahan.
Enggan bekerja dengan praktisi profesional
Komunikasi adalah masalah stimulus dan respons. Respons adalah semua impresi yang muncul dalam pikiran atau perasaan orang-orang tentang suatu hal — dalam hal ini, isyu yang kita usung. Stimulus adalah segala elemen sensoris dan pengalaman, baik yang sengaja dirancang atau tidak, baik datang langsung atau melalui orang lain, yang bisa menimbulkan berbagai respons tersebut.
Strategi berkaitan dengan menentukan respons yang tepat di orang yang tepat, melalui cara dan media yang tepat, dalam waktu yang tepat. Strategi adalah urusan logika (logic). Sementara kreativitas dan imajinasi dibutuhkan untuk menyusun stimulus yang bisa menggugah dan mengalahkan ketidakpedulian. Ini adalah magic yang melampaui logika.
Saya percaya bahwa peradaban maju antara lain karena ada spesialisasi, pembagian tugas, dan pertukaran sukarela antara para spesialis. Demikian pula halnya untuk membuat magic dari komunikasi publik organisasi masyarakat sipil. Apalagi saat ini, sudah banyak pekerja kreatif berkualitas yang bekerja mandiri. Platform atau marketplace yang mempertemukan antara pengguna jasa dan mereka pun sudah banyak di Indonesia, seperti FIverr, Upwork, Freelance.com, Projects.co.id, Sribulancer, dan Behance. Belum pernah organisasi masyarakat sipil punya pilihan sebanyak ini untuk menemukan praktisi profesional yang sesuai dengan anggaran dan kebutuhan, seperti saat ini.
Organisasi masyarakat sipil bisa mempunyai hubungan kerja yang produktif dengan praktisi profesional asalkan dari awal sudah memberi arahan (brief) yang jelas dan tidak berubah-ubah di tengah jalan. Seringkali dengan arahan yang baik, praktisi profesional akan tertantang atau terdorong untuk melibatkan diri dalam isyu ini. Dalam proses pembuatan output komunikasi, organisasi masyarakat sipil memberi umpan balik yang spesifik dan bertolak dari arahan, bukan dari selera dan asumsi pribadi. Dan tentu saja, ini semua percuma tanpa pembayaran dan proses yang transparan dan adil.
Kami mempunyai blanko arahan buat pekerja kreatif profesional yang bisa Anda gunakan. Jika Anda memerlukannya, Anda bisa meninggalkan pesan di situs kami. Namun Anda harus sudah mempunyai strategi komunikasi yang tajam dan lengkap untuk bisa mengisi blanko itu dengan baik.
Kesimpulannya: jika ingin lebih sering melakukan komunikasi publik yang ampuh mengakselerasi perubahan, organisasi masyarakat sipil mempunyai tiga pekerjaan rumah utama. Pertama, berhenti memperlakukan komunikasi publik sebagai anak bawang; kedua, mulai berinvestasi lebih serius untuk menyusun strategi komunikasi bersamaan dengan strategi program; dan terakhir, mulai mencoba untuk bekerja dengan praktisi profesional.
Godspeed, rebels.
Paramita Mohamad
Written by
CEO and Principal Consultant of Communication for Change. We work with those who want to make Indonesia suck less, by helping them get buy-in and make changes.
Related Articles