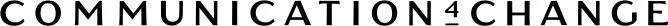Bisakah lembaga think tank menyelamatkan debat publik dari buzzer politik?
Ketika pemerintah memilih untuk memobilisasi propagandis media sosial daripada menggunakan bukti untuk menginformasikan kebijakan, apakah think tank dan organisasi masyarakat sipil memiliki kesempatan berjuang untuk mendorong reformasi yang sangat dibutuhkan?
Oleh Paramita Mohamad
12 Juni, 2020
12 Juni, 2020

Credit: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana, June 8, 2020
Pada saat Anda membaca tulisan ini, menyebutkan berbagai cara COVID-19 telah menjungkirbalikkan kehidupan kita sudah merupakan hal yang klise namun tetap perlu. Hal yang paling mengejutkan bagi saya adalah bagaimana ini membuat masalah-masalah yang belum terselesaikan di Indonesia menjadi semakin buruk, membuat pandemi dan dampaknya menjadi sangat buruk. Ketimpangan yang merajalela adalah contoh utama dari masalah-masalah tersebut, dan saya ingin menambahkan satu masalah lagi: memburuknya kualitas debat publik di Indonesia.
Pada hari-hari awal wabah, komunitas kesehatan masyarakat dan masyarakat sipil menuntut pemerintah untuk mendengarkan bukti-bukti berbasis sains dan memberlakukan karantina wilayah (lockdown) parsial melalui media sosial. Sementara itu, presiden secara terbuka menyatakan keengganannya untuk melakukan hal tersebut1, dan pemerintah lebih memilih untuk memberikan pengarahan kepada para influencer di media sosial (“buzzer”) untuk menyampaikan narasi terkait COVID-19 kepada publik2. Tak lama kemudian, para buzzer pro-pemerintah menyerang permintaan lockdown dan membingkainya sebagai taktik untuk meningkatkan peluang saingan politik presiden untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 20243,4,5. Perlu dicatat bahwa taktik pengalihan perhatian seperti ini telah digunakan sebelumnya, misalnya dalam mendorong revisi undang-undang yang membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi6.
Pola yang sama juga terlihat pada akhir Mei ketika akun-akun media sosial dalam jaringan Polri meluncurkan kampanye besar-besaran untuk mendorong “normal yang baru”, menelan keberatan dari para ahli kesehatan dan masyarakat yang cemas7.
Para aktor dari masyarakat sipil telah menyatakan kegelisahan mereka tentang bagaimana pemerintah telah mempersenjatai para buzzer untuk melawan para pengkritik8,9. Namun, ada baiknya kita menguraikan mengapa buzzer menjadi racun bagi debat publik dan dengan demikian berbahaya bagi demokrasi.
Para buzzer cenderung bekerja dengan cara “menyoroti” keluhan (“ini tidak otoriter”) atau menggunakan kekeliruan logika seperti ad-hominem (“para pengkritik adalah pendukung agenda pro-Islamisme”), false-dilemma (“kebebasan berkumpul atau Indonesiaku”), atau slippery-slope (“jika kita mulai membahas Papua, NKRI akan bubar”). Penggunaan taktik-taktik ini merupakan ciri khas argumentasi yang buruk dan tidak menyisakan ruang untuk bukti dan logika. Karena para buzzer ini memiliki audiens yang sangat besar, bisa dibilang mereka menetapkan norma-norma tentang debat publik, dan dengan demikian berkontribusi pada kehancurannya.
Ketika pemerintah lebih memilih untuk menggunakan propaganda media sosial daripada menggunakan bukti dari komunitas sains dan penelitian, apakah lembaga pemikir dan organisasi masyarakat sipil (OMS) memiliki kesempatan untuk mendorong reformasi yang sangat dibutuhkan?
Lembaga think-tank (saya merujuk pada OMS di bidang penelitian dalam diskusi ini) ada untuk memobilisasi keahlian dan ide untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Agar efektif, lembaga think-tank harus mampu menciptakan lingkungan sosial dan intelektual yang memaksa para pemangku kepentingan untuk berdebat dan menyadari bias-bias mereka sendiri. Mereka juga harus menyediakan sebuah kanal untuk memperkenalkan ide-ide baru dan memperluas cakupan debat publik10. Kanal tersebut harus mencakup media sosial, karena masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan rajin menggunakan media sosial11.
Saya pernah menyatakan bahwa bagi banyak lembaga think tank, komunikasi di media sosial belum diperlakukan sebagai bagian integral dari program. Media sosial lebih banyak digunakan untuk mengumumkan acara yang akan datang, menggantikan kartu ucapan, atau paling banyak untuk menyebarluaskan temuan atau analisis. Jika lembaga think tank terus melakukan hal ini, mereka menyia-nyiakan kesempatan untuk meningkatkan kualitas debat publik, memperkuat demokrasi, dan menciptakan iklim yang baik untuk advokasi mereka.
Bagaimana lembaga think-tank menggunakan media sosial mereka untuk mendorong dan meningkatkan debat publik? Hal ini berkaitan dengan praktik penulisan akademis yang mereka lakukan setiap hari. Tulisan akademis terbaik memiliki satu ciri utama: tulisan tersebut terlibat secara mendalam dengan pandangan orang lain12, seperti para akademisi lain di bidangnya.
Dengan kata lain, pada tingkat yang paling mendasar, konstruksi tulisan akademik yang persuasif dan menarik adalah “They say (kata mereka) / I say (kata saya)”. Oleh karena itu, untuk menjadi debat publik yang efektif, lembaga pemikir harus turut campur dalam percapakan yang sedang berlangsung, menggunakan pernyataan orang lain (“kata mereka”) sebagai landasan untuk menegaskan temuan dan bukti mereka (“kata saya”). Mereka harus menunjukkan sesuatu tentang argumen lain yang mereka dukung, tolak, perlu diperbarui, atau sesuai.
Berikut ini adalah contoh yang bagus dan terbaru dari SMERU Institute yang telah melakukan banyak penelitian tentang kemiskinan. Pada 5 Juni tahun ini, SMERU menanggapi cuitan seorang influencer dengan satu juta pengikut di Twitter yang menyatakan keberatannya tentang privilege yang digunakan untuk mengkerdilkan kesuksesan seseorang karena kerja keras lebih penting. SMERU menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan ketidaksetujuannya (secara santun) dan memperkenalkan studi mereka tentang kurangnya mobilitas sosial ke atas di kalangan masyarakat miskin di Indonesia. Interaksi ini mendapatkan respons yang luar biasa dari para netizen. Namun, yang lebih penting lagi, SMERU telah memperluas jangkauan perdebatan tentang kemiskinan struktural kepada mereka yang mungkin selama ini acuh tak acuh atau bahkan tidak tahu tentang besarnya ketimpangan di Indonesia.
Pada hari-hari awal wabah, komunitas kesehatan masyarakat dan masyarakat sipil menuntut pemerintah untuk mendengarkan bukti-bukti berbasis sains dan memberlakukan karantina wilayah (lockdown) parsial melalui media sosial. Sementara itu, presiden secara terbuka menyatakan keengganannya untuk melakukan hal tersebut1, dan pemerintah lebih memilih untuk memberikan pengarahan kepada para influencer di media sosial (“buzzer”) untuk menyampaikan narasi terkait COVID-19 kepada publik2. Tak lama kemudian, para buzzer pro-pemerintah menyerang permintaan lockdown dan membingkainya sebagai taktik untuk meningkatkan peluang saingan politik presiden untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 20243,4,5. Perlu dicatat bahwa taktik pengalihan perhatian seperti ini telah digunakan sebelumnya, misalnya dalam mendorong revisi undang-undang yang membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi6.
Pola yang sama juga terlihat pada akhir Mei ketika akun-akun media sosial dalam jaringan Polri meluncurkan kampanye besar-besaran untuk mendorong “normal yang baru”, menelan keberatan dari para ahli kesehatan dan masyarakat yang cemas7.
Para aktor dari masyarakat sipil telah menyatakan kegelisahan mereka tentang bagaimana pemerintah telah mempersenjatai para buzzer untuk melawan para pengkritik8,9. Namun, ada baiknya kita menguraikan mengapa buzzer menjadi racun bagi debat publik dan dengan demikian berbahaya bagi demokrasi.
Para buzzer cenderung bekerja dengan cara “menyoroti” keluhan (“ini tidak otoriter”) atau menggunakan kekeliruan logika seperti ad-hominem (“para pengkritik adalah pendukung agenda pro-Islamisme”), false-dilemma (“kebebasan berkumpul atau Indonesiaku”), atau slippery-slope (“jika kita mulai membahas Papua, NKRI akan bubar”). Penggunaan taktik-taktik ini merupakan ciri khas argumentasi yang buruk dan tidak menyisakan ruang untuk bukti dan logika. Karena para buzzer ini memiliki audiens yang sangat besar, bisa dibilang mereka menetapkan norma-norma tentang debat publik, dan dengan demikian berkontribusi pada kehancurannya.
Ketika pemerintah lebih memilih untuk menggunakan propaganda media sosial daripada menggunakan bukti dari komunitas sains dan penelitian, apakah lembaga pemikir dan organisasi masyarakat sipil (OMS) memiliki kesempatan untuk mendorong reformasi yang sangat dibutuhkan?
Lembaga think-tank (saya merujuk pada OMS di bidang penelitian dalam diskusi ini) ada untuk memobilisasi keahlian dan ide untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Agar efektif, lembaga think-tank harus mampu menciptakan lingkungan sosial dan intelektual yang memaksa para pemangku kepentingan untuk berdebat dan menyadari bias-bias mereka sendiri. Mereka juga harus menyediakan sebuah kanal untuk memperkenalkan ide-ide baru dan memperluas cakupan debat publik10. Kanal tersebut harus mencakup media sosial, karena masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan rajin menggunakan media sosial11.
Saya pernah menyatakan bahwa bagi banyak lembaga think tank, komunikasi di media sosial belum diperlakukan sebagai bagian integral dari program. Media sosial lebih banyak digunakan untuk mengumumkan acara yang akan datang, menggantikan kartu ucapan, atau paling banyak untuk menyebarluaskan temuan atau analisis. Jika lembaga think tank terus melakukan hal ini, mereka menyia-nyiakan kesempatan untuk meningkatkan kualitas debat publik, memperkuat demokrasi, dan menciptakan iklim yang baik untuk advokasi mereka.
Bagaimana lembaga think-tank menggunakan media sosial mereka untuk mendorong dan meningkatkan debat publik? Hal ini berkaitan dengan praktik penulisan akademis yang mereka lakukan setiap hari. Tulisan akademis terbaik memiliki satu ciri utama: tulisan tersebut terlibat secara mendalam dengan pandangan orang lain12, seperti para akademisi lain di bidangnya.
Dengan kata lain, pada tingkat yang paling mendasar, konstruksi tulisan akademik yang persuasif dan menarik adalah “They say (kata mereka) / I say (kata saya)”. Oleh karena itu, untuk menjadi debat publik yang efektif, lembaga pemikir harus turut campur dalam percapakan yang sedang berlangsung, menggunakan pernyataan orang lain (“kata mereka”) sebagai landasan untuk menegaskan temuan dan bukti mereka (“kata saya”). Mereka harus menunjukkan sesuatu tentang argumen lain yang mereka dukung, tolak, perlu diperbarui, atau sesuai.
Berikut ini adalah contoh yang bagus dan terbaru dari SMERU Institute yang telah melakukan banyak penelitian tentang kemiskinan. Pada 5 Juni tahun ini, SMERU menanggapi cuitan seorang influencer dengan satu juta pengikut di Twitter yang menyatakan keberatannya tentang privilege yang digunakan untuk mengkerdilkan kesuksesan seseorang karena kerja keras lebih penting. SMERU menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan ketidaksetujuannya (secara santun) dan memperkenalkan studi mereka tentang kurangnya mobilitas sosial ke atas di kalangan masyarakat miskin di Indonesia. Interaksi ini mendapatkan respons yang luar biasa dari para netizen. Namun, yang lebih penting lagi, SMERU telah memperluas jangkauan perdebatan tentang kemiskinan struktural kepada mereka yang mungkin selama ini acuh tak acuh atau bahkan tidak tahu tentang besarnya ketimpangan di Indonesia.
Hi Jerome, hal ini menarik untuk dibahas. Kisah sukses pada segelintir orang tidak bisa disamaratakan untuk semua kelompok. Dalam studi kami yang diterbitkan di @ADBInstitute, sangat jarang anak yang lahir dari keluarga miskin bisa sukses pada saat dewasa. https://t.co/bHH6q2MYaH
— The SMERU Research Institute (@SMERUInstitute) June 5, 2020
Sebuah contoh yang baik tentang bagaimana SMERU Research Institute menggunakan Twitter untuk memperluas perdebatan publik tentang privelege dan sulitnya mobilitas sosial di kalangan masyarakat miskin.
Contoh di atas mengilustrasikan bagaimana turut serta dalam percakapan yang tepat pada waktu yang tepat dapat membuat perbedaan. Lembaga think tank dapat mulai memantau percakapan yang sedang berlangsung yang berkaitan dengan program mereka dengan menggunakan analisis media sosial, yang memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi tidak hanya “apa” yang mereka katakan, tapi juga “siapa” mereka. Dengan eksplorasi tambahan, mereka dapat memetakan ketegangan moral atau nilai yang mendasari perdebatan, sehingga memungkinkan mereka untuk terlibat dalam percakapan secara lebih perseptif.
Selain memahami apa yang “mereka katakan”, lembaga pemikir dan OMS juga harus membangun kapasitas mereka untuk menyampaikan bagian “saya katakan”. Ada beberapa metode yang dapat dipelajari oleh semua orang, misalnya dari “They Say / I Say” : The Moves That Matter in Academic Writing (Graff dan Birkenstein, 2018). Selain itu, ada beberapa protokol yang dapat diterapkan oleh organisasi untuk membuat komunikasi media sosial lebih mudah dikelola namun tetap efektif untuk memajukan agenda mereka.
Selain memahami apa yang “mereka katakan”, lembaga pemikir dan OMS juga harus membangun kapasitas mereka untuk menyampaikan bagian “saya katakan”. Ada beberapa metode yang dapat dipelajari oleh semua orang, misalnya dari “They Say / I Say” : The Moves That Matter in Academic Writing (Graff dan Birkenstein, 2018). Selain itu, ada beberapa protokol yang dapat diterapkan oleh organisasi untuk membuat komunikasi media sosial lebih mudah dikelola namun tetap efektif untuk memajukan agenda mereka.

Banyak lembaga pemikir tidak mempekerjakan staf khusus untuk melakukan komunikasi, apalagi menjalankan akun media sosial mereka. Mereka mungkin harus menggalang dana tambahan untuk melakukan upaya ini dengan baik. Beberapa organisasi cukup beruntung untuk dapat menggunakan dana institusional, tetapi organisasi lainnya dapat mencoba memasukkan “memperkuat demokrasi atau pembuatan kebijakan yang inklusif melalui debat publik” ke dalam anggaran proyek.
Membendung memburuknya debat publik sangat mendesak di tengah kesibukan pemerintah untuk mencapai “normal baru”. “Normal baru” adalah salah kaprah. “Normal baru” terdistorsi oleh bias status quo yang terlihat jelas ketika orang lebih memilih untuk tetap melakukan hal yang sama dengan tidak melakukan apa-apa atau tetap bertahan pada keputusan yang telah dibuat sebelumnya13. Kita sekarang tahu bagaimana praktik-praktik yang menjadi norma sebelum virus corona telah membawa kita pada situasi sulit saat ini. Oleh karena itu, kita harus menolak “kenormalan baru” jika itu hanya merupakan eufemisme untuk “business as usual”.
Membangun kembali Indonesia pasca pandemi harus dengan ambisi yang lebih tinggi. Alih-alih “normal baru”, ambisi tersebut seharusnya adalah “perombakan besar”, di mana kita memperbaiki kesalahan atau kekeliruan di masa lalu dan memprioritaskan untuk mengatasi semua masalah mendasar yang membuat pandemi menghantam kita lebih keras. “Perombakan besar” membutuhkan kebijakan yang lebih baik dan pembuatan kebijakan yang lebih baik. Untuk mempengaruhi hal ini, aktor masyarakat sipil harus menjadi pendebat publik yang lebih baik.
Sudah saatnya lembaga think-tank dan organisasi masyarakat sipil beralih dari mengkritik buzzer menjadi melawannya, dan membuat bukti yang mereka hasilkan lebih relevan dan menarik bagi pemangku kepentingan yang lebih luas, terutama warga negara yang peduli.
Membendung memburuknya debat publik sangat mendesak di tengah kesibukan pemerintah untuk mencapai “normal baru”. “Normal baru” adalah salah kaprah. “Normal baru” terdistorsi oleh bias status quo yang terlihat jelas ketika orang lebih memilih untuk tetap melakukan hal yang sama dengan tidak melakukan apa-apa atau tetap bertahan pada keputusan yang telah dibuat sebelumnya13. Kita sekarang tahu bagaimana praktik-praktik yang menjadi norma sebelum virus corona telah membawa kita pada situasi sulit saat ini. Oleh karena itu, kita harus menolak “kenormalan baru” jika itu hanya merupakan eufemisme untuk “business as usual”.
Membangun kembali Indonesia pasca pandemi harus dengan ambisi yang lebih tinggi. Alih-alih “normal baru”, ambisi tersebut seharusnya adalah “perombakan besar”, di mana kita memperbaiki kesalahan atau kekeliruan di masa lalu dan memprioritaskan untuk mengatasi semua masalah mendasar yang membuat pandemi menghantam kita lebih keras. “Perombakan besar” membutuhkan kebijakan yang lebih baik dan pembuatan kebijakan yang lebih baik. Untuk mempengaruhi hal ini, aktor masyarakat sipil harus menjadi pendebat publik yang lebih baik.
Sudah saatnya lembaga think-tank dan organisasi masyarakat sipil beralih dari mengkritik buzzer menjadi melawannya, dan membuat bukti yang mereka hasilkan lebih relevan dan menarik bagi pemangku kepentingan yang lebih luas, terutama warga negara yang peduli.
Referensi
- Lockdown not yet an option for Indonesia, says President (2020, March 16), The Jakarta Post. Retrieved from https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/16/lockdown-not-yet-an-option-for-indonesia-says-president.html
- Puluhan “influencer” digandeng BNPB cegah COVID-19 (2020, March 21), Antara News. Retrieved from https://www.antaranews.com/berita/1371946/puluhan-influencer-digandeng-bnpb-cegah-covid-19
- Hermawan, A. (2020, March 21). Politics of pandemics: How online “buzzers” infect Indonesia’s democracy, jeopardize its citizens. The Jakarta Post. Retrieved from https://www.thejakartapost.com/academia/2020/03/21/covid-19-doesnt-care-about-politics-how-online-buzzers-infect-indonesias-democracy.html
- Sulaiman, Y. (2020, April 10). Indonesia’s politicisation of the virus is stopping effective response. Southeast Asia Globe. Retrieved from https://southeastasiaglobe.com/indonesia-covid-19-response/
- Warburton, E. (2020, May 28). Indonesia: Polarization, Democratic Distress, and the Coronavirus. Polarization and the Pandemic. Retrieved from Carnegie Endowment for International Peace website: https://carnegieendowment.org/2020/04/28/indonesia-polarization-democratic-distress-and-coronavirus-pub-81641
- Ristianto, C. Pakar Medsos: Ada “Buzzer” Pro-revisi UU KPK Gunakan Modus “Giveaway”(2019, September 18). Kompas.com. Retrieved from https://nasional.kompas.com/read/2019/09/18/13280691/pakar-medsos-ada-buzzer-pro-revisi-uu-kpk-gunakan-modus-giveaway
- Fahmi, I. (2020, June 9). Kampanye New Normal dan Reisa Effect? Slideshare. Retrieved from https://www.slideshare.net/IsmailFahmi3/kampanye-new-normal-dan-reisa-effect
- Damayana, G. P. (2019, October 3). ‘Buzzer’ dan Merawat Ruang Publik Kita. Retrieved June 9, 2020. Magdalene. Retrieved from: https://magdalene.co/story/buzzer-dan-merawat-ruang-publik-kita
- Saatnya Menertibkan Buzzer. (2019, September 28). Majalah Tempo. Retrieved from: https://majalah.tempo.co/read/opini/158488/saatnya-menertibkan-buzzer
- de Boer, J. (2015, March 17). What are Think Tanks Good for? Retrieved from United Nations University, Centre for Policy Research website: https://cpr.unu.edu/what-are-think-tanks-good-for.html
- Kemp, S. (2020, February 18). Digital 2020: Indonesia. Retrieved from DataReportal – Global Digital Insights website: https://datareportal.com/reports/digital-2020-indonesia
- Graff, G., & Birkenstein, C. (2018). “They say / I say” : the moves that matter in academic writing. New York ; London: W.W. Norton & Company.
- Samuelson, W., & Zeckhauser, R. J. (1988). Status quo bias in decision making. Journal of Risk and Uncertainty, 1, 7-59.
Paramita Mohamad
Written by
CEO and Principal Consultant of Communication for Change. We work with those who want to make Indonesia suck less, by helping them get buy-in and make changes.
Related Articles